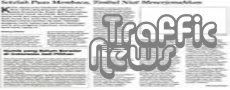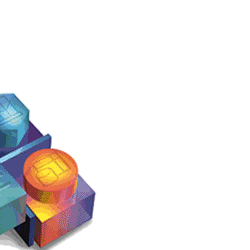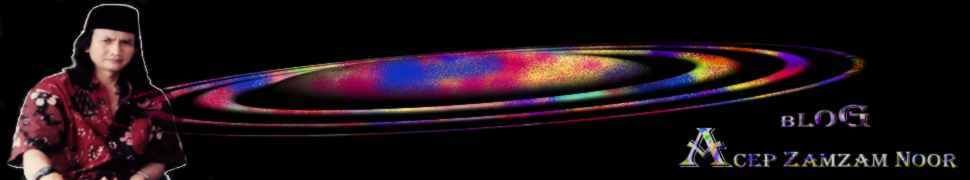Media Indonesia - SEJAK program substitusi minyak tanah ke elpiji digulirkan pemerintah tiga tahun yang lalu, sudah sekitar 100 ledakan gas elpiji terjadi di tengah masyarakat. Hingga saat ini belum jelas benar apa penyebab utama dari ledakan-ledakan gas elpiji tersebut. Namun, yang pasti ledakan baru bisa terjadi apabila ada gas elpiji yang bocor yang disambar api.
Boleh jadi ada botol elpiji, selang, dan regulator yang tidak memenuhi syarat-syarat keamanan SNI. Baik karena lolosnya botol-botol elpiji 'bodong', selang dan regulator yang di bawah standar, maupun karena umur pemakaian yang sudah melawati batas aman atau karena mutunya menurun karena handling distribusi yang kasar. Ataupun karena kelalaian pemakai elpiji itu sendiri. Kini 'ancaman' bayang-bayang ledakan gas elpiji menghantui masyarakat.
Untuk itu, pemerintah harus segera meningkatkan kontrol yang lebih ketat terhadap seluruh botol elpiji, terutama yang ukuran 3 kg, termasuk standar mutu selang dan regulator, sebelum diedarkan ke masyarakat. Tidak ada toleransi terhadap botol elpiji, selang, dan regulator yang tidak memenuhi syarat-syarat keamanan.
Sangat disayangkan, di tengah bunyi ledakan-ledakan kompor elpiji yang telah merenggut korban jiwa dan harta, dalam beberapa bulan ini, Pertamina mewacanakan untuk menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kg. Pertamina mengklaim rugi menjual elpiji nonsubsidi sehingga diusulkan untuk naik Rp1.000/kg. Namun, karena pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada Juli ini, rencana penaikan harga elpiji itu ditunda (Media Indonesia, 17 Juni 2010). Penaikan harga elpiji tinggal menunggu saat yang tepat.
Di sini, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah betul Pertamina mengalami kerugian dalam menjual elpiji nonsubsidi? Masalahnya, harga jual elpiji nonsubsidi yang dibayar masyarakat saat ini relatif sudah sangat mahal, selain Pertamina menggunakan acuan yang tidak lazim dalam menghitung besaran kerugian.
Menurut Pertamina, harga jual elpiji saat ini adalah Rp5.850/kg franco Pertamina. Apabila ditambahkan dengan biaya distribusi dan margin agen, harga yang dibayar masyarakat untuk elpiji botol 12 kg adalah Rp75.000/botol atau sekitar Rp6.250/kg. Dengan kurs US$1 = Rp9.074 dan nilai panas (heating value) dari 1 kg elpiji = 44.000 BTU, dalam ukuran nilai panas, harga elpiji nonsubsidi 12 kg yang dibayar masyarakat menjadi sekitar US$15,65/mmbtu.
Jelas itu merupakan harga yang sangat mahal bila dibandingkan dengan harga gas Tangguh di Papua yang dijual pemerintah ke China dengan harga US$3,35/mmbtu. Dengan kata lain, harga gas elpiji 12 kg yang dibayar masyarakat adalah sekitar 460% (hampir lima kali lipat) dari harga jual gas Tangguh ke China! Apakah Pertamina dan pemerintah akan tetap 'tega' menaikkan harga elpiji untuk rakyatnya, sedangkan gas milik negara di Papua dijual ke China dengan harga seperlimanya?
Apakah betul Pertamina rugi menjual elpiji 12 kg?
Di dalam prinsip akuntansi biaya yang paling dasar, untuk menghitung apakah penjualan suatu produk menguntungkan atau merugikan biasanya digunakan rumusan yang sangat sederhana. Yakni membandingkan antara harga jual (selling price) dan biaya pokok penjualan (cost of good sold). Apabila harga jual berada di bawah biaya, dikatakan bahwa perusahaan itu mengalami kerugian dan sebaliknya, apabila harga jual di atas biaya, perusahaan itu dikatakan memperoleh keuntungan.
Rupanya, rumusan yang sangat sederhana dan berlaku universal ini ternyata tidak berlaku di dalam menghitung/menentukan apakah penjualan elpiji oleh Petamina mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Untuk menghitung jumlah 'kerugian', Pertamina membandingkan harga jual dengan harga pasar internasional, bukan membandingkan harga jual dengan biaya.
Itu terlihat dari 'kegenitan' Pertamina yang selalu mengekspos ke masyarakat bahwa Pertamina menanggung kerugian dari penjualan elpiji 12 kg dengan mengacu kepada harga elpiji di pasar internasional, yakni contract price (CP) Aramco. Padahal kalau mengacu kepada biaya pokok elpiji, amat mungkin Pertamina tidak mengalami kerugian. Malah dengan harga jual saat ini, boleh jadi Pertamina sudah memperoleh keuntungan.
Untuk 2010, dengan mengacu kepada harga CP Aramco sebesar US$718/metric ton dan US$1 = Rp9.074, harga keekonomian (= harga pasar) elpiji dalam negeri menjadi Rp8.508/kg franco Pertamina. Dengan begitu, kalau harga elpiji tidak dinaikkan, Pertamina mengklaim akan mengalami kerugian sebesar Rp3,19 T.
Penggunaan harga pasar internasional (CP Aramco) sebagai dasar perhitungan untung-rugi, baru benar apabila seluruh (100%) dari elpiji yang dijual Pertamina berasal dari elpiji impor. Namun faktanya, tidak semua elpiji berasal dari impor.
Elpiji yang dijual di dalam negeri, sebagian besar berasal dari produksi elpiji dalam negeri, baik merupakan produk sampingan dari kilang BBM maupun dari kilang elpiji. Mestinya, Pertamina harus menghitung besaran biaya pokok elpiji dalam negeri. Biaya pokok itu pasti jauh lebih rendah daripada harga elpiji pasar internasional. Mengapa?
Untuk elpiji yang berasal dari kilang BBM, bahan bakunya berasal dari minyak mentah (crude oil), yang produk utamanya adalah BBM, sedangkan elpiji merupakan produk ikutan. Dengan demikian, meskipun bahan baku minyak mentah relatif mahal karena mengikuti harga minyak dunia, biaya pokok elpiji pasti akan murah karena merupakan produk ikutan. Sementara itu, elpiji yang berasal dari kilang elpiji, bahan bakunya adalah gas alam dan harga gas di kepala sumur (well-head) relatif murah, jauh di bawah harga ekspor LNG. Dengan begitu, biaya pokoknya akan relatif sangat murah.
Oleh karena itu, klaim Pertamina mengalami kerugian dalam menjual elpiji kiranya perlu dikoreksi/diluruskan dengan cara menggunakan acuan yang lazim. Gunakanlah acuan biaya pokok tertimbang yang proporsional dengan jumlah elpiji produksi dalam negeri dengan jumlah elpiji yang berasal dari impor.
Sebenarnya strategi bisnis Pertamina untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan kerugian adalah upaya yang sangat wajar bagi sebuah PT (persero). Namun, upaya tersebut sebaiknya dilakukan secara benar dan konsisten.
Kalau Pertamina konsisten dengan prinsip tersebut, mestinya pengembangan dan pemasaran lapangan gas Donggi Senoro (DS) di Sulawesi Tengah misalnya, mestinya dilakukan sendiri oleh Pertamina. Sebagaimana yang pernah dilakukan Pertamina dalam mengembangkan lapangan gas yang dioperasikan kontraktor asing di Badak, Kalimantan Timur, dan di Arun, Aceh. Pengembangan lapangan gas model LNG Badak dan Arun yang dilakukan Pertamina telah terbukti selama 30 tahun telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi negara (APBN).
Sebagai gambaran bahwa pada 2008 misalnya, penerimaan APBN dari hasil penjualan gas/LNG ke luar negeri yang dikembangkan sendiri oleh Pertamina mencapai sekitar Rp100 T atau sekitar sepertiga dari total penerimaan migas yang mencapai sekitar Rp300 T. Itu memberikan hasil maksimal untuk negara.
Namun, ternyata di dalam pengembangan lapangan gas DS yang notabene merupakan lapangan yang dioperasikan sendiri oleh Pertamina dan Medco, justru oleh pimpinan Pertamina diserahkan kepada pihak lain (konsorsium dengan mayoritas saham 'milik' Mitsubishi). Itu patut dipertanyakan sebab akan muncul lubang inefisiensi yang menganga lebar dengan potensi keuntungan Pertamina dan potensi pendapatan negara akan hilang dan berpindah ke Konsorsium Mitsubishi. Berapakah perkiraan kasar dari potensi keuntungan yang hilang ini?
Dengan asumsi harga minyak rata-rata sekitar US$90/bbls selama 15 tahun usia proyek DS, Konsorsium Mitsubishi sebagai pihak yang diserahi Pertamina dalam mengembangkan DS, akan menjual LNG DS ke Jepang dengan harga sekitar US$15/mmbtu.
Sementara itu, Mistsubishi hanya membayar sekitar US$7/mmbtu kepada Pertamina sebagai operator/pemilik lapangan gas. Setelah dikurangi dengan biaya pencairan gas (sekitar US$1/mmbtu) dan ongkos angkut ke Jepang (sekitar US$1/mmbtu), perkiraan potensi keuntungan Pertamina dan negara yang akan berpindah ke Konsorsium Mitsubishi menjadi sekitar US$6/mmbtu. Kalau jumlah penjualan LNG DS ke Jepang sebesar 2,0 juta ton/tahun, potensi keuntungan Pertamina dan pendapatan negara yang berpindah ke konsorsium Mistsubishi menjadi sekitar = US$6 x 88 juta mmbtu = US$528 juta/tahun. Karena di dalam Konsorsium Mitsubishi juga ada share 49% dari Pertamina dan Medco, perkiraan potensi neto keuntungan Pertamina dan pendapatan negara yang berpindah ke Mitsubishi menjadi sekitar US$269 juta/tahun atau sekitar US$4.039 miliar selama 15 tahun.
Potensi keuntungan yang hilang itu bisa dihindari jika Pertamina konsisten sebagai PT (persero) yang berusaha memaksimumkan keuntungan dengan jalan mengembangkan sendiri lapangan gas DS dengan mekanisme pembiayaan outsourcing yang dikoordinasikan dengan calon pembeli. Sebagaimana halnya Pertamina membiayai pembangunan pabrik LNG Badak dan Arun pada 1970-an.
Strategi bisnis yang dianut pimpinan Pertamina belakangan ini dengan menciptakan lubang-lubang inefisiensi patut dipertanyakan. Mengapa Pertamina begitu antusias untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan elpiji dalam negeri? Sementara itu, dalam pengembangan lapangan gas miliknya sendiri justru prinsip memaksimumkan keuntungan tidak diterapkan? Padahal Pertamina, selain berpengalaman dalam memasarkan LNG, sangat berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan pabrik LNG.
Daripada gas DS diserahkan kepada Konsorsium Mitsubishi untuk diekspor, tentu lebih baik apabila seluruh gas DS diperuntukkan untuk dalam negeri. Baik untuk keperluan pembangkit listrik, pabrik pupuk, sebagai bahan bakar gas (BBG) untuk substitusi premium di sektor transportasi maupun untuk memenuhi kebutuhan elpiji dalam negeri.
Dari sisi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan regulator, usulan Pertamina untuk memberlakukan 'harga keekonomian' yang tidak lain adalah merupakan 'harga pasar dunia', akan menggiring pemerintah pada posisi sulit. Bak makan buah simalakama. Pasalnya, justru pemerintah (Kementerian ESDM) sendiri yang menyetujui penjualan LNG Tangguh ke China dengan harga supermurah US$3.35/mmbtu atau sekitar 20% dari harga elpiji dalam negeri.
Dari sini terlihat pemerintah cenderung akan 'lepas tangan' atas usulan Pertamina tersebut dengan menyerahkan kembali masalah penaikan harga elpiji kepada Pertamina sebagai kebijakan korporasi. Padahal urusan elpiji 12 kg terkait dengan hajat hidup orang banyak dan tata niaganya merupakan monopoli negara (c/q Pertamina) sehingga semestinya kendali harga ada di tangan pemerintah bukan dilempar balik ke Pertamina.
Apakah tepat untuk menggiring harga elpiji yang dibutuhkan rakyat banyak supaya mengikuti harga elpiji/gas dunia, sedangkan gas milik negara di Tangguh, Papua, dijual pemerintah (Kementerian ESDM) ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dan tidak boleh mengikuti perkembangan harga gas/minyak dunia? Silakan dijawab dengan hati nurani.
Oleh Dr Kurtubi Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Pengajar Pascasarjana FEUI, Alumnus Colorado School of Mines (CSM) Denver, dan Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs (ENSPM) Paris
Labels: Kemelut