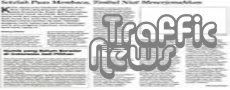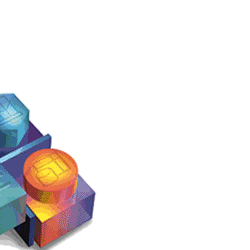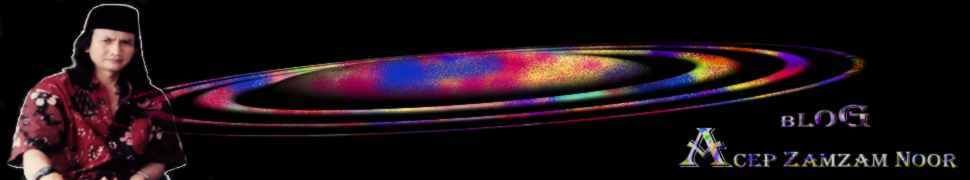PUISI DAN PIDATO
Acep Zamzam Noor
KANG Maman harus bersyukur karena tak lama setelah mondok di berbagai pesantren ia berhasil menyunting seorang gadis manis asal Jatiwangi. Kang Maman harus bersyukur karena tak lama setelah menyunting gadis manis itu, ia merintis sebuah pesantren bersama mertuanya yang pengusaha restoran. Kang Maman harus bersyukur karena tak lama setelah merintis pesantren dan mendirikan madrasah ia kemudian banyak diundang orang untuk memberikan ceramah. Kang Maman harus bersyukur karena selain fasih mengutip ayat-ayat suci, ceramah-ceramahnya pun segar, penuh kelakar dan selalu diakhiri dengan doa yang membuat orang menangis. Kang Maman harus bersyukur karena setelah ceramah-ceramahnya diminati banyak orang ia kemudian dipanggil kiai. Kang Maman harus bersyukur karena setelah dipanggil kiai, ia berkenalan dengan Ahmad Syubbanuddin Alwy. Kang Maman juga harus bersyukur karena setelah berkenalan dengan Ahmad Syubanuddin Alwy, tentu saja ia kemudian bersentuhan dengan puisi.
Mempunyai kemampuan berpidato adalah sebuah anugerah, begitu juga kemampuan menulis puisi. Dipanggil orang kiai adalah sebuah kehormatan, begitu juga dipanggil penyair. Antara kiai dan penyair ada perbedaan namun banyak juga persamaannya. D. Zawawi Imron, seperti yang kita kenal, penyair asal Madura ini puisi-puisinya sangat religius dan mutunya diakui para kritikus. Selain menulis puisi, ia juga banyak mengisi kolom-kolom keagamaan di berbagai media. Ia sangat akrab dengan K.H. A. Mustofa Bisri, juga dengan kiai-kiai terkenal lainnya. Tentu saja ia sangat fasih mengutip ayat-ayat suci karena memang jebolan pesantren. Tapi berbeda dengan kebanyakan mubalig yang sudah dipanggil kiai dalam usia muda, Zawawi Imron baru dipanggil kiai setelah usianya melewati angka 55.
Sementara Abdul Hadi W.M. yang tulisan-tulisan keagamaannya sangat menyentuh, puisi-puisi sufistiknya sangat menggetarkan serta kajian-kajian teologi maupun tasawufnya sangat mendalam, belum juga dipanggil kiai meskipun rambutnya sudah memutih semua. Begitu juga dengan Taufiq Ismail, yang semua orang tahu puisi-puisinya selalu menyeru pada kebenaran dan memerangi segala macam kemungkaran. Penyair ini juga dikenal sangat alim, taat beribadah, suka memakai peci, sering pergi ke tanah suci dan tidak pernah keluyuran malam hari. Namun entah kenapa sampai saat ini belum ada yang memanggilnya kiai.
Sebenarnya sebutan kiai tidak selalu ada hubungannya dengan kealiman atau ketaatan beribadat seseorang. Juga tidak selalu ada hubungannnya dengan ilmu agama atau dunia kepesantrenan. Sebutan kiai terdapat juga pada budaya yang sedikit banyak punya hubungan dengan dunia mistik. Dalam tradisi Jawa banyak benda-benda pusaka seperti gamelan, keris, pedang, tombak, kereta kencana sampai peralatan dapur dinamai kiai. Begitu juga dengan binatang-binatang piaraan yang dianggap keramat seperti gajah, kerbau atau kuda. Bahkan sebutan kiai juga bisa ditujukan kepada pohon beringin, tempat-tempat angker seperti hutan atau bukit. Di keraton Yogyakarta semua benda pusaka dinamai kiai, begitu juga dengan binatang piaraan. Di pinggiran kota Magelang ada sebuah bukit yang dinamai Kiai Langgeng, konon karena di bukit tersebut ada sebuah makam keramat.
Dengan demikian sebutan kiai bukan hanya milik orang yang dianggap menguasai ilmu agama saja. Dalang, pemusik karawitan, penari tradisional, pendekar silat, dukun atau orang pintar juga biasa disebut kiai atau kadang hanya disingkat “ki” saja. Sebutan kiai atau ki muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap benda, binatang atau manusia yang dianggap keramat dan diyakini bisa memberikan berkah atau kebaikan pada orang banyak. Begitu juga sebutan kiai dalam dunia kepesantrenan. Sebutan kiai tidak hanya diberikan pada orang yang alim saja, namun lebih-lebih pada mereka yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk masyarakat. Seorang yang berilmu tinggi namun tidak mau menerjunkan diri ke tengah masyarakat tidak akan pernah dipanggil kiai.
Dalam konteks ini sebutan kiai menjadi semacam anugerah atau gelar kehormatan untuk seseorang yang dianggap berjasa pada masyarakat. Seseorang yang menjadi tempat bertanya, tempat mengadu dan berlindung masyarakat di sekitarnya. Seseorang yang telah mampu mencerahkan masyarakatnya dalam banyak hal. Seseorang yang telah menjadi “sesuatu” yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentu saja pihak yang pantas memberikan anugerah atau gelar tersebut hanyalah masyarakat, bukan pemerintah, bukan universitas, bukan media massa, juga bukan pesantren apalagi diri sendiri seperti yang banyak terjadi belakangan ini.
Maka jelaslah kenapa Abdul Hadi W.M. yang rambutnya sudah memutih semua masih belum dipanggil kiai. Kenapa Taufiq Ismail yang dikenal sangat alim, taat beribadat dan lewat puisi-puisinya selalu mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, juga tak kunjung dipanggil kiai. Sementara Emha Ainun Nadjib yang jauh lebih muda (tentu saja rambutnya lebih gondrong) dibanding kedua penyair senior tadi malah sering dipanggil kiai, meski dengan mebel-embel mbeling. Cerita mungkin akan lain seandainya Abdul Hadi W.M. dan Taufiq Ismail aktif juga berkhotbah, memberikan ceramah agama, mengisi pengajian di masjid-masjid atau mengasuh majlis ta’lim.
Sumber http://budayaacepzamzamnoor.blogspot.com/2009/07/artikel-7.html
Labels: Baris, Iklan, Iklan Baris Koran Via SMS, Koran, SMS, via